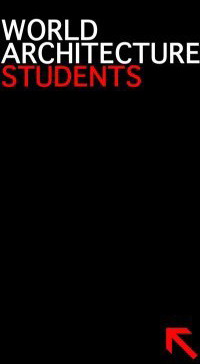Sementara Muzdalifah yang masih mengganjalkan jempol kakinya pada kaki meja itu tampak turut tersenyum-senyum mendengar obrolan keduanya. Muzdalifah begitu merasa terhormat kedatangan dua tamu tersebut. Karenanya ia merasa sangat senang. Menurut adiknya, Siti Arofah, kedua tamu itu sangat pintar dalam urusan mengajar Al-Qur’an. Bahkan, Muzdalifah sempat merasa malu ketika si adik bermata belo itu menjelaskan kepadanya mengenai definisi betapa indahnya belajar membaca Al-Qur’an. Waktu itu Siti Arofah menuturkan; “Dalam kata ‘masjidun’ cuma ada empat huruf; ma, sin, jim, dan dal. ‘Ma’ berarti; tempat. Sin, jim, dan dal satu kalimat yang dibaca ‘sajada’ aritinya; bersujud. Jadi; masjidun itu berarti; sebuah tempat untuk bersujud. Begitu kata Kak Alin sama Kak Anthi!” Duh Ampun, ingin sekali saat itu Muzdalifah turut serta belajar mengaji bersama adiknya. Tapi, perasaan tidak pantas membuat hasratnya harus disimpan baik-baik. Siang ini, Kak Anthi maupun Kak Alin yang diceritakan adiknya tersebut tengah berada di hadapannya. Berkunjung seraya menyantap kue bikinannya. Alangkah gembiranya hati Muzdalifah menyadari hal tersebut. Ditambah ketika Kak Alin berbicara memuji:
“Enak sekali kue koci kukusnya. Bumbu kelapanya sagat manis dan gurih. Bolehlah berbagi resep…?!” katanya tersenyum menggoda.
“Lifah juga diajari Umi, Kak.” Elak Muzdalifah malu-malu.
Lalu Kinanthi menyambung:
“Apapun yang kita dapat itu semuanya dari Umi, Emak, Bapak, Abah, atau Mama. Toh mereka juga sama seperti kita-kita sekarang. Mendapat pengetahuan ya dari orang-orang tua mereka juga, kan?!” katanya.
“Betul Nona. Seratus buat kamu. Tapi…” sebelum Fauz Lin melanjutkan, Kinanthi buru-buru menengadahkan tangan. Fauz Lin yang mengerti maksud sahabatnya meralat sambil menahan tawa:
“Seratusnya tidak jadi. Bisa bangkrut lama-lama kalau begini caranya.”
Tangan kiri Kinanthi mencubit lengan sahabatnya , lalu merekapun tertawa bersamaan.
Muzdalifah berkhayal; seandainya saja dirinya kelak menjadi bagian dari mereka? Ah, betapa senangnya bercanda tawa dengan penuh keakraban yang sangat manis. Tapi, khayalan-khayalan seperti itu kemudian meragukan kemungkinannya. Muzdalifah merasa, selama ia tumbuh dewasa dan menjadi bagian dari masyarakat kampungnya tidak ada satupun komunitas anak sebayanya yang menampilkan peran. Adapun kehadiran Fauz Lin dan Kinanthi hanya baru beberapa bulan setelah mereka tidak pernah ada di desa ini. Mungkin, pengaruh yang dibawanya dari luar desa memancing keberaniannya untuk menembus batas-batas sosial yang memisahkan antara kaum perempuan dengan laki-laki; mereka cenderung takut-takut. Untunglah, sekembalinya Kyai Ma’ruf dari perantauannya di daerah Lampung sana dapat mengubah sedikit penerimaan ide serta gagasan Fauz Lin maupun Kinanthi. Muzdalifah percaya, dibawah kepemimpinan Kyai Ma’ruf akan lebih mewadahi aspirasi yang muncul ketimbang Kyai Bashiron yang terkesan kolot dan keukeuh akan sikap anti pemikiran baru. Muzdalifah bertanya dalam hati; “Apa mungkin saya bisa seperti mereka? Bersosial, dan berperan?” di dalam hati Muzdalifah masih belum begitu yakin akan perubahan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di kampungnya. Muzdalifah tahu, sudah begitu banyak generasi-generasi baru yang sudah menamatkan pendidikan tinggi di desanya. Tapi, apakah pendidikan itu bisa dikatakan cukup untuk merubah pola kekolotan desanya? Ataukah tujuan pendidikan itu hanya sebatas untuk menyelamatkan masing-masing diri? Muzdalifah jadi teringat kata-kata Akhwan ketika dirinya menyarankan Akhwan untuk turut bermusyawarah di Masjid. Ketika itu, Akhwan berbalik menyarankan; “Kamu masih kecil. Jangan terlalu turut campur memikirkan permasalahan desa ini. Tidak ada untungnya samasekali.” “Mungkin ada benarnya kata Kak Akhwan.” bisik hati Muzdalifah. Tak sadar, nama sepupunya yang baru saja diucapkannya dalam hati begitu saja meluncur, tanpa beban, dan baru terasa setelah ia berpikir-pikir akan sikap Akhwan yang sudah membuatya resah. “Duh…” Demi menghargai kedua tamunya, Muzdalifah segera menyimpan kegelisahannya yang tiba-tiba muncul tersebut. Seraya bersuara menghilangkan lendir di tenggorokan, Muzdalifah membereskan letak duduk lalu kembali menghadapi Fauz Lin dan Kinanthi.
Sementara itu, Fauz Lin yang sempat menunda perbincangan menegur Muzdalifah dengan berkata:
“Seharusnya kamu bersyukur punya Umi yang begitu tauladan pada anaknya. Kalau dipikir-pikir, hanya resep-resep warisan seperti ini yang kita dapatkan dari mereka. Selebihnya…??” kedua mata Fauz Lin melirik pada sahabatnya, Kinanthi.
Lalu Kinanthi menyambung:
“Selebihnya ada di sini, dan di sini!” ucapnya seraya mengarahkan jari telunjuk pada pelipis lalu berpindah ke dada.
Fauz Lin sanang sekali jika sahabatnya sudah mulai terpancing untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Karena tanpa disadari oleh Kinanthi, dirinya telah begitu banyak mengasah kepekaan dari penuturan-penuturan sahabatnya itu. Hingga, dalam beberapa saat, baik dirinya maupun Muzdalifah tidak ada yang bersuara untuk menunggu penuturan Kinanthi.
Selesai meneguk air putih dari gelas bening, Kinanthi lalu berujar:
“Membuat kue itu ibarat sebutir serpihan gergaji. Sebenarnya jauh lebih banyak yang dituturkan oleh orang-orang tua kita dulu. Pendidikan moril contohnya. Orang-orang tua kita begitu luwes menyampaikan maksud baiknya melalui perumpamaan-perumpamaan meski tidak jarang terlalu susah diterima akal.” “Apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, dalam mendidik dengan cara mereka sendiri, itu bukanlah sebuah metoda yang tanpa alasan. Baiklah aku setuju, jika orang-orang tua kita mengatakan; ‘Anthi! Jangan makan brutu! Nanti kamu bisa menyesal di belakang.’ Memang orang selalu menyesal dibelakang, dan itu kedengarannya naif dan terkesan membodoh-bodohi. Bahkan kemungkinan besar orang tua yang berkata seperti itu hanya didasari oleh sikap takut akan ‘pamali’ terhadap orang tuanya. Tapi, kita yang lebih diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan, tidak juga pantas mengatakan itu naif dan bodoh. Melainkan kita mesti lebih bijak menghormati kata ‘pamali’ tersebut.”
“Contohnya?” tanya Fauz Lin.
Kinanthi melanjutkan:
“Kata ‘pamali’ memang bukan larangan dari Tuhan. Itu hanyalah kata ganti untuk dosa adat. Tapi jika itu dilanggar, kita sudah termasuk membuat kesalahan berkali-kali. Pertama kita tidak mau tahu dengan metoda pendidikan luhur orang tua kita, yang kedua kita menjadi tidak takut lagi untuk berbuat kurang ajar terhadap orang tua, dan yang ketiga, yang paling parah, kita sebagai generasi telah membunuh habis citra kita sebagai bangsa yang bercorak. Kalau sudah demikian, apakah nanti ada yang bisa membedakan mana orang Lemah Wangi, mana orang kota yang menjajah tradisi?”
Written by; Adhe Su Herman